
Perjuangan Para Mama dalam Menghadapi Pembangunan Waduk Lambo
Pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2025, Hermina Mawa (51) kembali mengenang bagaimana pembangunan Waduk Lambo di Nusa Tenggara Timur secara perlahan mengikis kehidupan masyarakat adat di tempat ia tumbuh sejak remaja. Di Kasepuhan Guradog, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, Banten, ia bercerita tentang arti tanah bagi komunitasnya. “Bagi kami, tanah adalah Ibu,” tuturnya.
Berjarak sekitar 2.300 kilometer dari tempat ia berasal, Hermina menceritakan bagaimana kondisi kebun, ternak, dan segala yang hidup di atasnya berangsur hilang. “Kalau yang senasib pasti menangis, dan memberi saya support,” kata dia.
Dalam kurun delapan tahun terakhir, ia dan para mama di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesa Selatan, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur berjuang mempertahankan tanah ulayat mereka dari pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo.
Pembangunan Waduk Lambo merupakan wacana yang kembali mengemuka setelah terkubur cukup lama. Pembangunan di Lowo Se, tanah hak ulayat masyarakat adat Rendu, Ndora, dan Lambo ini mulai bergulir pada 2001. Namun kala itu, penolakan dari masyarakat setempat langsung bergolak hingga pemerintah pusat membatalkan rencana tersebut.
Lantas pembangunan kembali muncul empat belas tahun kemudian. Penolakan masih terjadi. Menurut Hermina, masyarakat sempat menawarkan lokasi alternatif untuk pembangunan waduk sehingga tidak mengusik tanah ulayat dan tempat tinggal masyarakat. Namun seiring waktu, pemerintah melalui pihak kontraktor bahkan melibatkan aparat saat melakukan survei lokasi. Sejumlah bentrok pun terjadi.
September 2021, Hermina masuk dalam daftar enam orang yang dipanggil untuk mengikuti pemeriksaan oleh Kepolisian Resor Nagekeo ihwal keterlibatannya menolak pembangunan Bendungan Mbay Lambo di Lowo Se. Pada 4 Oktober 2021, Hermina juga sempat diborgol aparat saat menggelar aksi penolakan ritual di titik nol proyek Waduk Lambo. “Saya diborgol, masyarakat ditangkap polisi, yang lebih saya ingat, kehidupan saya sudah hilang.”
Pada Desember 2021 juga sempat kembali ada bentrok dengan aparat yang membuat sejumlah mama melepas pakaian dan bertelanjang dada akibat ada kekerasan yang mereka terima.
Setidaknya sejak 2016 hingga April 2024 perjuangan para mama itu berlangsung. Kini, Hermina memang tak lagi menempati rumah lamanya. Ia dan warga lain harus pindah ke kawasan relokasi, berjarak sekitar satu kilometer dari kampung yang sudah mereka tinggali turun-temurun.
Meski sudah menetap di area baru, mereka masih tinggal di Dusun Malapoma, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, NTT. Melakukan relokasi pada akhirnya bukan lagi pilihan. Pasalnya, pemerintah sudah harus segera membangun waduk yang semula ditargetkan rampung pada 2024. Pembangunan tertunda karena gelombang penolakan warga cukup besar sehingga proses pembangunannya molor dari rencana semula.
Lokasi tempat Hermina dan sejumlah warga Rendubutowe akan menjadi desa pertama yang terendam saat waduk sudah terbangun. Itu mengapa, Kepala Desa Rendubutowe, Yeremias Lele, akhirnya meminta pada pemangku adat untuk bisa merelokasi sejumlah kepala keluarga ke area tanah ulayat yang masih kosong dan belum digarap. Menurutnya, lokasi tersebut cukup aman sebagai tempat tinggal baru sejumlah warga walau masih dekat area waduk.
Dalam sejumlah sosialisasi menurutnya tidak pernah ada pembahasan jelas soal relokasi. Sehingga menurut Yeremias, tidak nampak siapa yang semestinya bertanggung jawab untuk memindahkan warga terdampak. Belum lagi, pembahasan soal ganti rugi tanah pun belum tuntas.
Yeremias mengaku tidak pernah terlibat dalam bahasan penentuan nilai tanah. Ia mengakui penetapan nilai ganti rugi begitu rendah, Rp 30.500 per meter. Penghitungannya hanya berdasar luas tanah. Sedangkan rumah, ternak, pohon, tanaman pangan, termasuk kuburan keluarga dan leluhur tidak turut dihitung padahal semuanya memiliki nilai.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dwi Purwantoro menyebut proses pengadaan tanah untuk Waduk Lambo melalui skema ganti untung berupa uang tunai, sehingga masyarakat melakukan relokasi secara mandiri. “Artinya saat musyawarah bentuk ganti kerugian yang disepakati antara pemilik dan pelaksana pengadaan tanah adalah dalam bentuk uang,” tutur Dwi, pada Sabtu.
Menurutnya, proses pengadaan tanah tidak menghitung jumlah kepala keluarga, tetapi jumlah bidang tanah. Pemerintah menargetkan pembebasan 1.124 bidang dengan total luas 988,09 hektare. Dwi menjamin Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) bersertifikat menentukan nilai ganti kerugian melalui hasil appraisal. Namun, pemerintah menunda sebagian pembayaran karena harus memvalidasi dokumen kepemilikan tanah. “Untuk menghindari potensi kerugian negara, mengingat banyak dokumen kepemilikan tanah yang perlu dilakukan pencermatan.”
Sampai saat ini, pemerintah desa merelokasi sekitar 111 kepala keluarga. Masing-masing KK mendapatkan lahan 80 meter persegi untuk dimanfaatkan mendirikan rumah, menggarap kebun, dan memelihara ternak jika ada. Hermina, kini tinggal di rumah berkerangka dan dinding bambu milik mamanya, Imelda Dheta yang sudah sepuh. “Mama memang minta untuk kami tinggal bersama, jadi saya sendiri tidak membangun rumah,” tutur Hermina. Saat ini sudah ada 21 rumah yang sudah berdiri dan dibangun swadaya oleh masyarakat. "Dari 21 baru 11 rumah yang terisi. Sisanya masih tinggal di rumah lama," ujar dia.
Dari belakang rumahnya, Hermina bisa melihat bagaimana pembangunan waduk berlangsung. Tanah lapang yang dulunya hijau tempat sejumlah ternak dilepas untuk merumput, kini hanya jadi lapang gersang dengan sejumlah alat berat mengeruk dan meratakan tanah. Pepohonan pun perlahan berganti beton. Tiap memandang ke kawasan pembangunan waduk, dada Hermina kerap bergolak. “Sampai saat ini saya masih belum bisa pergi ke titik nol (sebutan untuk area pembangunan waduk),” tutur Hermina tercekat. “Saya masih belum rela,” tuturnya lagi.
Area relokasi masyarakat Dusun Malapoma, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesa Selatan, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Yeremias Lele
Hermina bahkan masih mengingat bagaimana mama Imelda meraung saat perwakilan pihak PT. Brantas Abypraya, kontraktor pelaksana pembangunan Bendungan Lambo, datang ke rumah sekitar Juli tahun lalu. “Ketika orang-orang dari proyek ini datang ke rumah lama menyampaikan akan cabut pohon alpukat dan jeruk itu, mama menangis seperti ada orang yang meninggal,” ujar Hermina.
Selama tinggal di tempat relokasi menurut Hermina, Mama Imelda kerap bersedih. Namun ia akan menangis jika berkunjung ke rumah lama yang kini sudah kosong.
Baik hermina dan warga lainnya memang masih kerap bolak-balik ke rumah lama mereka. Ada yang menyicil angkut barang, ada pula yang masih melakukan sejumlah aktivitas seperti bertenun. Pasalnya, para mama belum bisa menenun di area relokasi karena belum mengadakan upacara adat. Sedangkan untuk melakukan upacara adat juga tidak mudah dan butuh biaya cukup besar. “Untuk relokasi dan kembali membangun rumah saja kami sudah sangat berat,” ujar Hermina.
Tenun dan Anyaman yang Turut Terusik
Para perempuan di Desa Rendubutowe memegang banyak peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Di ladang, mereka menanam, berkebun, dan beternak selayaknya kegiatan yang banyak dilakukan para laki-laki. Di rumah, mereka mengurus keluarga dan menenun. “Ini hanya boleh dilakukan para perempuan saja,” tutur Rosina Wonga, 53 tahun.
Rosina juga merupakan warga Desa Rendubutowe. Namun lokasinya tinggal tidak termasuk area yang mengalami relokasi. Sehingga, sampai saat ini, Mama Ros, begitu ia biasa dipanggil, masih bisa menenun kain di rumah. Menurut Rosina, biasanya, kain tenun mereka buat setelah pulang dari kebun, di sela waktu luang, atau ketika hujan yang membuat mereka berdiam di rumah.
Namun, ketika konflik pembangunan waduk muncul, aktivitas menenun ikut berpindah tempat. Beberapa mama membawa alat tenun ke posko penjagaan. Di sana, di atas balai-balai bambu, mereka menenun sambil berjaga agar perwakilan perusahaan tidak bisa menerobos masuk untuk melakukan survei. Tempo menyaksikan hal tersebut langsung saat berkunjung ke posko penjagaan pada 2021. Saat itu para mama bergiliran jaga setelah paginya bekerja di ladang.
Rosina Wonga, 53 tahun, masyarakat adat Rendu sedang menenun di rumahnya di Dusun Malapoma, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dok. Pribadi
Selain kain, tangan-tangan para mama juga menghasilkan anyaman. Mereka membuat tikar, bore, keterampilan anyaman khas Nagekeo. Lalu mbola, wadah khas untuk menyimpan hasil ladang dan panen seperti beras, jagung, dan lainnya, serta berbagai perlengkapan adat. Namun, pembangunan waduk lagi-lagi mempengaruhi aktivitas tersebut. Pasalnya, bahan baku anyaman adalah daun pandan dan lontar yang turut berkurang seiring pembangunan berlangsung. “Sekarang kami mau buat anyaman juga sulit. Bahannya seperti pandan dan lontar habis kena gusur semua,” tutur Ros.
Menurut Ros, kain tenun yang biasanya bisa ia jual hingga Rp 1 juta perlembar, kini harus ia lepas berapa pun nilainya, selama ada yang mau membeli. Saat ini karena lahan dan ternak sudah terganggu, suami para mama yang biasa di ladang terpaksa menganggur. Beban menanggung kebutuhan rumah tangga pun turut bertumpu di pundak para mama.
Saat kebutuhan harian makin mendesak, Rosiana dan banyak mama lain makin tak punya pilihan. “Padahal dulu untuk kebutuhan makan kami tinggal ambil dari kebun. Uang dari menjual tenun bisa kami simpan atau untuk biayai sekolah anak,” ujar Ros.
Padahal menenun butuh proses panjang dari membentang benang, membuat motif, menyelup dalam pewarna alami, dan sejumlah proses lain sampai akhirnya proses tenun dimulai. Setidaknya butuh satu bulan untuk menyelesaikan selembar kain, bergantung kerumitan motif dan ukuran. Makin rumit dan panjang, makin banyak waktu yang para mama butuhkan.
Selain harus memikirkan kebutuhan rumah tangga, para mama juga tak lepas bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Apalagi di NTT, peran seorang perempuan dianggap sebagai pilar dan penerus generasi. Dalam tradisi, posisi para perempuan diakui melalui belis, pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan.
Janji Manis Pemerintah
Waduk atau Bendungan Mbay-Lambo merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diatur dalam Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional pada era Presiden Joko Widodo.
Menurut Jokowi, pembangunan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Waduk mulai dibangun akhir 2021 dengan kapasitas tampung hingga 51 juta meter kubik air, ditargetkan mampu mengairi 4.200 hektare lahan sawah, ditambah pengembangan 1.900 hektare. Jokowi berharap bendungan ini dapat mendorong produksi beras di Nagekeo hingga 2,5 kali lipat, atau meningkat 250 persen.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dwi Purwantoro mengakui, pembangunan Waduk Lambo akan menggunakan sebagian lahan warga sebagai lokasi genangan. Namun, menurut dia, setelah bendungan terisi dan beroperasi, waduk ini diproyeksikan memberi banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Layanan irigasi akan meningkat dari 4.289 hektare menjadi 6.240 hektare, sementara Indeks Pertanaman naik dari 225 persen menjadi 300 persen. Selain itu, waduk ini akan menyediakan air baku sebesar 205 liter per detik.
“Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan air baku, untuk budidaya perikanan tangkap dan ada potensi untuk tenaga listrik tenaga air serta dapat dikembangan untuk pariwisata.”
Perlawanan yang selama ini ditunjukkan masyarakat dan para mama menurut Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Nusa Bunga Maximilianus Herson Loi lantaran berkaca pada sejarah pembangunan waduk di Indonesia.
Semuanya menunjukkan pola yang nyaris selalu sama. Pembangunan Kedung Ombo di Jawa Tengah, Koto Panjang di Sumatera, hingga Jatigede di Jawa Barat, selalu menjanjikan kesejahteraan dan kemakmuran. Namun warga di tepian waduk lantas hidup dalam keterhimpitan ruang hidup dan ekonomi, serta kehilangan akses pada sumber pangan.
Yang Hilang karena Pembangunan
Begitu pembangunan mulai, sejumlah lahan berladang dan padang luas untuk melepas ternak perlahan lenyap. Terutama bagi masyarakat yang mengalami relokasi. Di tempat baru, masing-masing keluarga menerima lahan sekitar 20x40 meter untuk menampung rumah kebun, dan juga kandang ternak.
Menurut Rosina, belakangan tanaman yang tumbuh di kebun pun perlahan berkurang. Padahal, walau terlihat seperti tanah gersang, karakter tanah di Nagekeo dengan batuan kapur atau vulkanik cocok untuk tanaman pangan dan perkebunan. Itu mengapa, di atasnya bisa tumbuh jali, jagung solor, wijen, padi, kacang-kacangan, pisang, juga singkong.
Selain itu juga tanaman untuk bahan anyaman seperti pandan dan lontar, serta tanaman jangka panjang, yakni jambu mete, kemiri, mangga, jeruk, alpukat, jati, dan mahoni. “Hasil kebun saat itu kami bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi,” kenang Ros.
Berdasarkan yang ia ingat, Ros merinci bagaimana saat panen, kemiri sempat laku terjual di kisaran Rp 30-40 ribu per kilo. Lalu, dalam hitungan masing-masing perkilonya, jambu mete bisa terjual Rp 15-20 ribu, jagung Rp 10 ribu, beras Rp 15 ribu, wijen Rp25-30 ribu, kacang hijau Rp 30 ribu, kacang tanah Rp 35 ribu, dan singkong Rp 10 ribu per kilo.
Sementara dari ternak, masyarakat bisa menjual Rp 5 juta per ekor, kerbau Rp 10-20 juta bergantung ukurannya, dan kambing sekitar Rp 1 juta per ekor. “Dari jaman nenek moyang kami hanya bekerja hanya bercocok tanam dan beternak,” tuturnya.
Saat ini meski beberapa di rumah sudah mulai bisa bercocok tanam area relokasi, jumlah tanaman hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Kadang ada yang datang untuk membeli cabai, terung, daun ubi," tutur Hermina, namun menurutnya harganya tidak seberapa.
Seperti Hermina, Rosina juga belum bisa membayangkan bagaimana ia memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. “Sudah dari dulu profesi kami seperti itu dan kalau harus mengubah profesi tidak seperti membalik telepak tangan,” tuturnya tegas.
Sampai saat ini, di area relokasi juga belum berlangsung upacara adat untuk mengawali kehidupan baru. Tak cuma itu, banyak makam keluarga dan leluhur yang dulunya hanya berjarak beberapa langkah dari rumah lama, kini tertinggal di wilayah dan terancam tergenang.
Sedangkan untuk memindahkan makam, biayanya setara dengan pemakaman baru. “Kami harus memperlakukan sama persis saat melakukan upacara pemakaman,” kata Hermina. Padahal untuk mengadakan upacara pemindahan makam itu di luar kemampuan ekonomi banyak keluarga. “Makam-makam itu sakral,” tuturnya lagi.
Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Nusa Bunga Maximilianus Herson Loi memerikan, bagi masyarakat adat suku Rendu, tanah adalah ibu. “Merusak tanah sama halnya merusak harkat dan martabat kaum ibu. Maka patut untuk dijaga dan diselamatkan,’ ujarnya, Jumat lalu.
Itu mengapa menurut Herson, para mama menempati peran penting dalam perjuangan. Apalagi, kehilangan tanah dan lahan garapan sudah pasti berdampak pada ekonomi rumah tangga yang bakal terasa langsung oleh para mama. “Jangan heran jika peran kaum ibu atau kaum perempuan dalam perjuangan sangat kuat. Itu karena mereka tahu perempuan yang paling rentan dan yang paling merasakan dampaknya,” ujar Herson.
Herson menambahkan, pembangunan waduk membuat masyarakat kehilangan lahan garapan, padang penggembalaan, dan tempat ritus. Kasus serupa turut terjadi di sejumlah daerah yang menenggelamkan ribuan hektare lahan, hutan, dan sawah.
Menurut dia, pembangunan Waduk Lambo juga terlihat mulai merusak tatanan kehidupan masyarakat adat. Proyek ini menghilangkan lahan garapan, padang penggembalaan, dan tempat ritus, sekaligus memaksa masyarakat adat direlokasi. Relokasi tidak hanya memindahkan tempat tinggal, tetapi juga memutus kehidupan yang telah mereka bangun. “Dengan segala keterbatasan, orang akan memulai kehidupan baru di tempat baru. Relokasi ini membuat masyarakat adat itu merasa kehilangan identitas.”
Dengan kondisi sebagian besar sungai di Indonesia yang rusak dan curah hujan semakin tidak menentu, menurut dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Yuki M.A. Wardhana, waduk memang berperan penting menjaga ketersediaan air sepanjang tahun, baik untuk irigasi maupun kebutuhan air baku.
Selain itu menurutnya, Waduk juga menahan volume air sungai agar tidak langsung mengalir ke laut. Jika air tawar sudah terbuang ke laut, biaya mengolahnya menjadi air bersih bisa 2 hingga 3 kali lebih mahal dibanding memanfaatkan air tawar langsung.
Yuki tak memungkiri, pembangunan waduk bisa menimbulkan dampak lingkungan karena mengubah fungsi lahan. Jika sebelumnya kawasan berupa hutan, maka fungsi ekosistem hutan hilang dan berganti dengan fungsi waduk dalam siklus hidrologi.
Dampak lain yang kerap muncul adalah konflik sosial, terutama karena masyarakat harus menyerahkan tempat tinggal mereka untuk area waduk. Menurut dia, semestinya risiko sosial ini bisa dimitigasi dan dianalisis dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang menjadi dasar penerbitan Penlok dan dokumen AMDAL. “Pada penyusunan dua dokumen tersebut, komunikasi atau konsultasi publik dengan masyarakat menjadi wajib dilaksanakan,” tutur Yuki saat dihubungi pada Sabtu, 23 Agustus.
Para perempuan adat Rendu, Lambo dan Ndora saat di pos jaga di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur/Dokumentasi Hermina Mawa
Masalahnya, peran masyarakat tidak sepenuhnya hadir dalam proses tersebut. Hal itu yang kerap memicu terjadi konflik. Bahkan pembahasan mengenai ganti rugi memecah suara masyarakat. Ada pihak yang mendapatkan ganti rugi besar padahal tidak begitu terdampak langsung pembangunan waduk. “Ada yang hanya kebun padahal kami dengan tempat tinggal,” tutur Hermina. Masalah itu saja menurutnya membuat sejumlah kelompok masyarakat sampai saat ini tidak lagi bertegur sapa.
Semenjak pembangunan dimulai, menurut Hermina dan Rosina, sudah tidak ada lagi perkumpulan atau perlawanan. Upaya saling meberi dukungan menurutnya hadir saat berjumpa di acara gereja.
Masyarakat sudah berfokus untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada juga menurut Hermina yang merasa sudah kalah hingga akhirnya terpaksa untuk mengikuti maunya pemerintah.
Namun ia yakin, kini semua akan terus berjuang dengan jalannya sendiri. Karena keberlangsungan hidup bergantung pada bagaimana para mama bertahan menjaga hidup, adat, dan tanah ulayat. “Kami akan terus berjuang. Saya tidak merasa sudah kalah. Tidak sama sekali,” tutur Hermina.



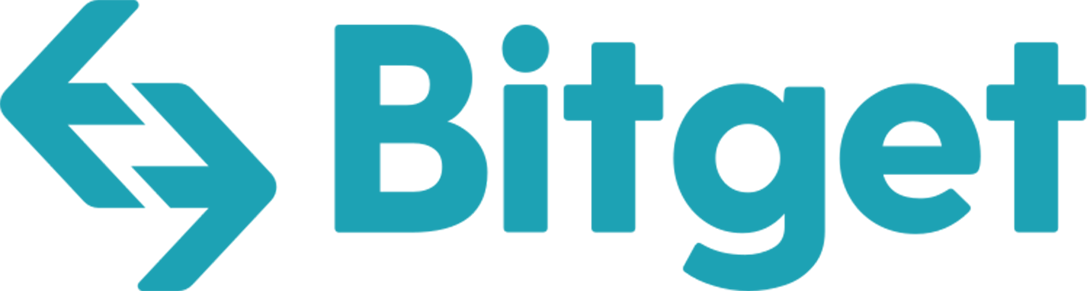

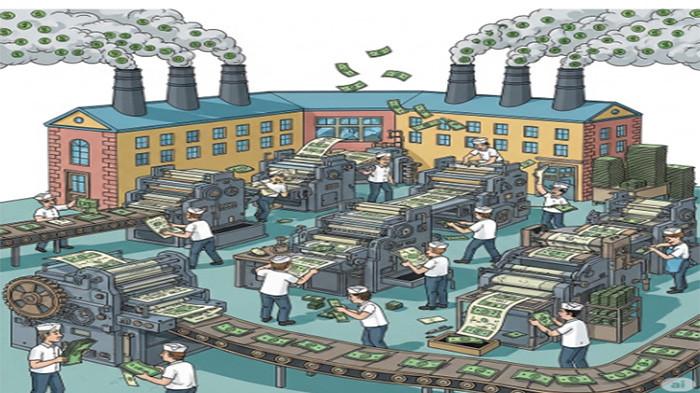
















Komentar
Tuliskan Komentar Anda!