
Sejarah dan Tantangan Solusi Dua Negara untuk Palestina
Solusi dua negara, yang sering dianggap sebagai jalan keluar dari konflik Israel-Palestina, memiliki sejarah panjang yang terkait dengan berbagai peristiwa politik dan diplomasi. Pemikiran ini pertama kali muncul pada akhir masa Mandat Inggris atas Palestina, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan pembagian wilayah tersebut menjadi negara Yahudi dan Arab pada tahun 1947. Namun, rencana ini ditolak oleh warga Palestina, yang melihatnya sebagai pencaplokan tanah mereka oleh kelompok Zionis.
Setelah perang 1948, negara-negara Arab tetangga Palestina menyatakan perang dan solusi dua negara tidak pernah diwujudkan. Gencatan senjata 1949 menetapkan bahwa Yordania menguasai Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sedangkan Mesir menguasai Gaza. Israel kemudian merebut wilayah-wilayah tersebut dalam perang 1967. Solusi dua negara yang saat ini digagas meminta kembalinya perbatasan sebelum 1967.
Upaya Membentuk Negara Palestina
Sejarah pengakuan negara Palestina juga memiliki cerita panjang. Pada 1948, Pemerintahan Seluruh Palestina (APG) didirikan di Gaza dan mengklaim kedaulatan atas seluruh Mandat Palestina. Namun, APG hanya bisa beroperasi di Jalur Gaza setelah koloni pemukim Israel dibentuk. Akhirnya, APG membubarkan diri pada tahun 1953 karena tekanan dari Barat dan keterlibatan dalam pembagian wilayah antara Israel dan Raja Abdullah I dari Yordania.
Pada 1988, Dewan Nasional Palestina secara sepihak mendeklarasikan "kemerdekaan" di Aljazair. Meskipun puluhan negara mengakui negara merdeka ini, Amerika Serikat menolaknya. AS dikenal sebagai pihak yang bertanggung jawab menghalangi kemerdekaan Palestina. Pada 1947, AS menekan beberapa negara untuk mengubah suara mereka pada menit-menit terakhir dan mendukung Resolusi Majelis Umum PBB 181 tentang Rencana Pemisahan Palestina. AS juga memastikan untuk tidak mengakui APG.
Perjanjian Oslo pada 1993-94 berujung pada pembentukan Otoritas Palestina (PA), serta negosiasi dengan Israel mengenai isu-isu inti seperti kemerdekaan, perbatasan, Yerusalem, dan kembalinya pengungsi. Namun, proses ini tidak pernah terwujud. Bahkan, ancaman AS dan pemerintah Arab pro-Amerika membuat Presiden PA Yasser Arafat membatalkan rencananya untuk mendeklarasikan kemerdekaan.
Pengakuan Internasional dan Kebijakan AS
Hingga Mei 2025, 143 negara dari 193 negara di dunia telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat setidaknya setengah lusin pada bulan ini, termasuk mitra utama kejahatan Israel: Perancis, Kanada, Australia, dan Inggris, serta Belgia, Portugal, Malta, dan mungkin Finlandia. Namun, AS tetap mempertahankan posisi yang diambilnya sejak 1948: mencegah Palestina mendirikan negara khayalan, apalagi negara nyata.
Perdana Menteri Italia Georgia Meloni mengkritik proyek pengakuan tersebut, dengan alasan bahwa "mengakui Negara Palestina sebelum didirikan dapat menjadi kontraproduktif". Ia sepakat dengan pandangan bahwa mengakui negara Palestina yang belum memiliki wilayah berdaulat adalah omong kosong. Sebaliknya, negara-negara Eropa dan Arab percaya bahwa pengakuan Palestina adalah cara terbaik untuk membatasi aspirasi Palestina dan menggagalkan perjuangan mereka untuk pembebasan menjadi ilusi kenegaraan yang tidak mengancam supremasi Yahudi Israel.
Perspektif dari Tokoh-Tokoh Politik
Joseph Massad, profesor politik Arab modern dan sejarah intelektual di Universitas Columbia, New York, menekankan bahwa satu-satunya cara bagi negara-negara ini untuk menghukum Israel secara diplomatis adalah dengan menarik pengakuan atas hak Israel untuk menjadi negara supremasi Yahudi, dan memboikotnya serta menerapkan sanksi internasional terhadap Israel sampai Israel menghapuskan semua undang-undang rasisnya. “Jika tidak demikian, keseluruhan konferensi ini hanyalah sia-sia dan merupakan bukti lebih lanjut dari keterlibatan para peserta dalam genosida Israel terhadap rakyat Palestina.”
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak solusi dua negara atas dasar nasionalistik dan keamanan. Basis agama dan nasionalis Netanyahu memandang Tepi Barat sebagai tanah air orang-orang Yahudi yang alkitabiah dan bersejarah, sementara orang-orang Yahudi Israel sebagian besar menganggap Yerusalem sebagai ibu kota abadi mereka. Kelompok garis keras Israel seperti Netanyahu berdalih bahwa Palestina tidak menginginkan perdamaian.
Pandangan Para Perunding Veteran
Para perunding veteran seperti Hussein Agha dan Robert Malley menyimpulkan bahwa solusi dua negara adalah bagian dari sandiwara. “Solusi dua negara tidak akan pernah bisa memuaskan salah satu pihak,” kata Agha dan Malley. Mereka berargumen bahwa proses perdamaian Israel-Palestina dibangun di atas harapan khayalan. Yang lebih mendesak, menurut mereka, adalah mengakhiri pembantaian di Gaza dengan memberikan hukuman nyata kepada para pelaku pembantaian yang sedang berlangsung.
Agha dan Malley berdalih bahwa pandangan bahwa dua negara merupakan satu-satunya solusi adalah pola pikir yang malas dan akan melanggengkan status quo. “Pilihan binari antara satu negara bagian dan dua negara bagian yang terpisah adalah salah dan tidak perlu. Terdapat beragam kemungkinan diantaranya, suatu spektrum yang mencerminkan gradasi kedaulatan dan derajat otonomi agama atau etnis.” Mereka menyarankan agar kita sadar bahwa konflik ini pada dasarnya bukan soal wilayah, tetapi tentang orang-orang, kehidupan mereka, emosi, kemarahan, kesedihan, keterikatan, dan sejarah.





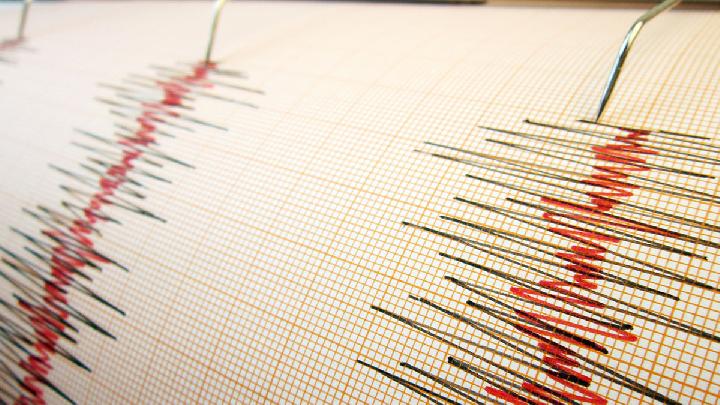



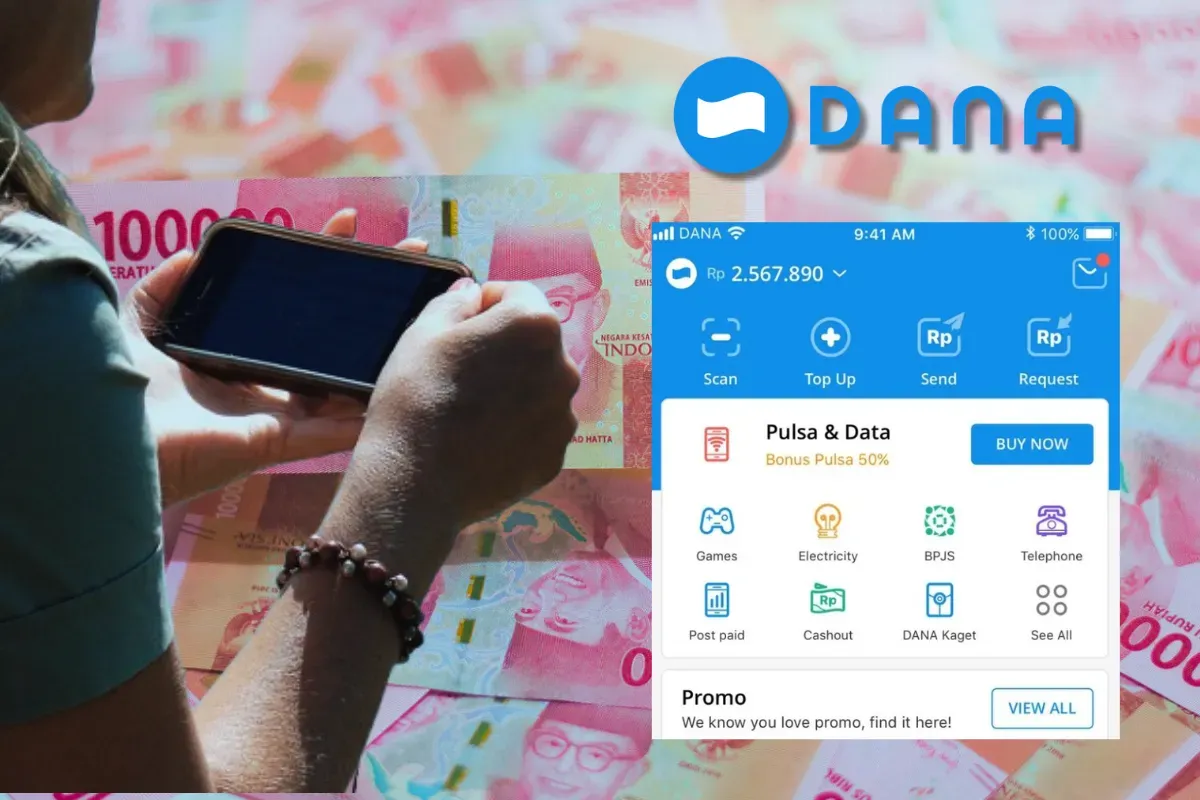












Komentar
Tuliskan Komentar Anda!