
Peristiwa Mengejutkan di Nepal dan Keterkaitannya dengan Demonstrasi Besar
Peristiwa yang terjadi di Nepal pada awal tahun 2025 menunjukkan bahwa ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya generasi muda, bisa terpicu oleh berbagai faktor. Meski tidak sepenuhnya sama dengan demonstrasi besar-besaran di Indonesia, peristiwa tersebut memiliki kesamaan dalam hal akar masalah dan dampak yang signifikan.
Pemicu utama dari kegaduhan di Nepal adalah kebijakan pemerintah yang melarang akses ke sekitar 26 platform media sosial besar, termasuk Facebook, X (Twitter), YouTube, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Keputusan ini diambil pada awal September 2025 setelah perusahaan-perusahaan tersebut gagal mematuhi tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk mendaftarkan diri dan menetapkan kantor di Nepal.
Media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan Gen Z. Dengan akses yang tiba-tiba dibatasi, para pemuda di Nepal merasa ruang digital mereka dikurangi. Hal ini memicu kemarahan yang akhirnya berujung pada unjuk rasa besar-besaran, terutama di Kathmandu, yang berubah menjadi bentrokan yang menyebabkan korban jiwa.
Pemerintah Nepal mengklaim bahwa larangan ini bertujuan untuk mengatasi penyebaran misinformasi dan hate speech, serta mengontrol platform-platform tanpa regulasi jelas. Namun, banyak pengamat dan kelompok hak asasi manusia melihat ini sebagai bentuk sensor dan pembungkaman kebebasan berekspresi.
Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi bentuk perlawanan yang lebih keras. Aparat keamanan menggunakan gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam, sehingga jumlah korban meningkat. Ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam hal korupsi, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.
Larangan media sosial bukan hanya penyebab langsung dari demonstrasi, tetapi juga simbol dari ketegangan antara generasi muda dan pemerintah. Platform media sosial telah menjadi sarana utama bagi generasi muda untuk menyuarakan kritik, menyebarkan informasi, dan mengorganisir aksi. Ketika akses itu dicabut, muncul persepsi bahwa negara sedang menyerang ruang digital yang mereka anggap milik bersama.
Krisis harga kebutuhan pokok, seperti bahan makanan dan energi, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat turun ke jalan. Inflasi yang tidak seimbang dengan pertumbuhan pendapatan rumah tangga membuat masyarakat kelas menengah ke bawah dan miskin semakin terdesak secara sosial dan ekonomi.
Selain faktor ekonomi, ada dimensi struktural di dalam masyarakat Nepal yang memperburuk situasi. Sistem politik yang rapuh sering kali gagal memberikan respons cepat terhadap kebutuhan rakyat. Elite politik kerap terjebak dalam persaingan kekuasaan yang dangkal, sementara kebijakan publik yang pro-rakyat gagal dihadirkan.
Ketidakpuasan publik terhadap korupsi, birokrasi yang lamban, dan kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan turut menambah frustrasi generasi muda. Kombinasi ini melahirkan persepsi bahwa negara tidak hadir untuk melindungi dan bekerja demi rakyatnya di dalam masa krisis.
Demonstrasi yang berujung kerusuhan di Nepal mencerminkan akumulasi ketidakpuasan sosial-ekonomi yang sudah cukup dalam dan lama. Masalah-masalah ini berpadu dengan lemahnya kapasitas negara dalam mengelola demonstrasi. Aparat keamanan sering kali bertindak represif, yang justru memperburuk ketegangan dan memicu eskalasi kerusuhan.
Dari perspektif sosial-ekonomi, demonstrasi masif di Nepal merepresentasikan jurang ketidaksetaraan yang makin menganga. Pertumbuhan ekonomi Nepal lebih banyak dinikmati oleh kalangan terbatas di perkotaan, sementara sebagian besar masyarakat kelas bawah dan pedesaan masih hidup dengan keterbatasan infrastruktur, layanan kesehatan, akses pendidikan bahkan pangan.
Efek domino dari gerakan demonstrasi masif di Indonesia jelang akhir Agustus lalu juga terlihat di negara-negara seperti Filipina, Thailand, dan Nepal. Negara-negara yang pemerintahannya dianggap cenderung korup, oligarkinya kuat, atau politik dinastinya menonjol, cenderung terimbas efek domino.
Salah satu indikasi efek domino tersebut di Nepal adalah bendera One Piece yang digunakan oleh demonstran muda sebagai simbol perlawanan terhadap sensor dan korupsi pemerintah. Gen Z di Nepal, seperti di tempat lain, tumbuh di era digitalisasi global dan memiliki ekspektasi pada mobilitas sosial yang lebih baik. Namun, ketika harapan tersebut berbenturan dengan realitas struktural, maka terbentuklah kesadaran kolektif untuk melawan.
Dari perspektif teori ruang publik Jürgen Habermas, media sosial berfungsi sebagai arena deliberasi dan artikulasi kepentingan publik. Bagi Gen Z, tak terkecuali di Nepal, platform digital seperti Facebook, Instagram, dan X bukan sekadar alat komunikasi, tetapi ruang politik yang memungkinkan mereka membangun identitas, solidaritas, dan narasi tandingan terhadap negara.
Dengan kata lain, ketika ruang komunikasi formal dibatasi, generasi muda akan mencari kanal ekspresi alternatif melalui aksi kolektif, yang berpotensi berujung kerusuhan jika keresahan sudah mencapai titik “kemuakan kelas dewa”. Laurie Rice dan Kenneth Moffett dalam buku mereka, “The Political Voices of Generation Z”(2021), mengafirmasi mengapa Gen Z cenderung tidak sama dengan generasi sebelumnya dalam berekspresi, karena mereka lebih progresif dan berani.
Gen Z, kata Rice dan Moffett, memiliki orientasi politik yang cenderung lebih progresif dibandingkan generasi Milenial maupun generasi X. Dari sisi pandangan, Gen Z lebih terbuka terhadap keberagaman, lebih peduli pada inklusivitas, dan lebih getol menuntut transparansi dari institusi politik. Bahkan kedua penulis ini menemukan bahwa tingkat kepercayaan Gen Z terhadap institusi tradisional, seperti partai politik dan lembaga pemerintah, cenderung rendah.
Singkat kata, pemerintah harus menyadari bahwa Generasi Z kini menjadi penentu utama dalam politik. Untuk meraih kepercayaan penuh dari generasi ini, perlu adanya perbaikan di segala lini, serta benar-benar menyentuh akar persoalan, agar “grievances” dari Gen Z tidak berubah menjadi “Revenge”.



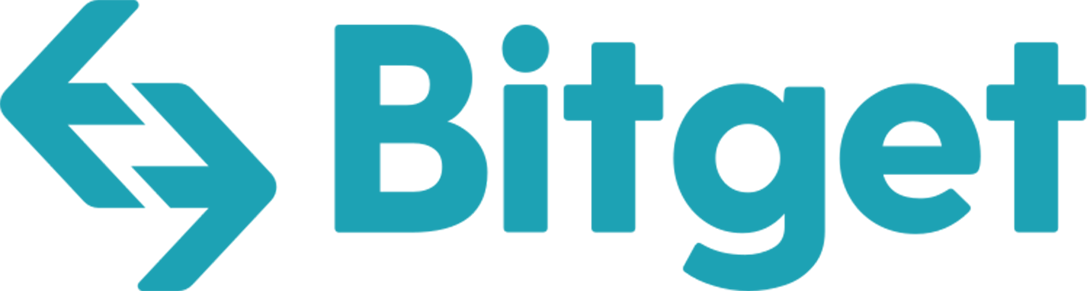



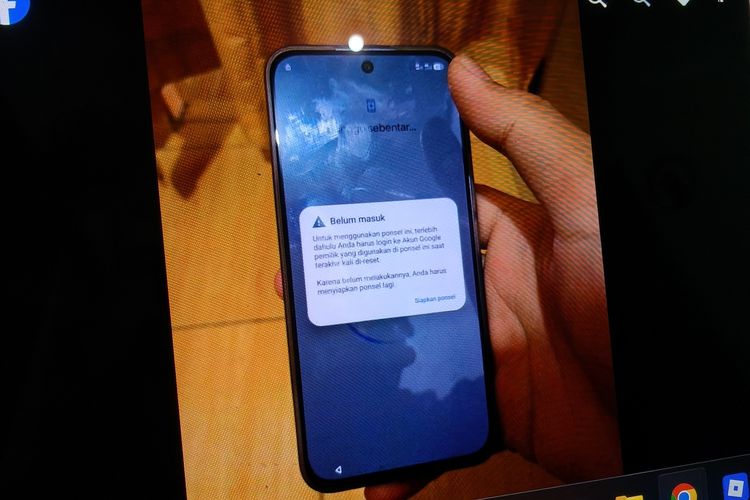













Komentar
Tuliskan Komentar Anda!