
Kathmandu, 5 September -- Pakaian cepat (fast fashion) secara diam-diam sedang mengubah cara masyarakat Nepal berbelanja dan berpakaian. Dari tren yang dipengaruhi TikTok hingga banjir impor murah dari Tiongkok, India, dan Thailand.
Seperti budaya 'pakai dan buang' yang menyebar lebih cepat dari sebelumnya, muncul gelombang baru minat industri yang berpotensi memperparah krisis tersebut. Dengan Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi terhadap pakaian dari India dan Bangladesh, merek internasional kini mulai memandang Nepal sebagai pusat produksi pakaian berbiaya rendah berikutnya. Perusahaan-perusahaan India juga melihat Nepal sebagai peluang. Namun, apa yang tampaknya menjadi potensi ekonomi ini menyimpan risiko yang berat. Bagi sebuah negara yang sudah kesulitan dengan sampah dan regulasi yang lemah, kombinasi konsumsi pakaian cepat dan produksi pakaian industri bisa berarti polusi, eksploitasi, serta masa depan yang lebih mirip krisis pakaian Bangladesh daripada sebuah kisah sukses.
Ini bukan hanya debat tentang kebijakan perdagangan atau peluang bisnis. Ini tentang seberapa cepat pakaian cepat (fast fashion) membentuk kehidupan, lingkungan, dan ekonomi di Nepal. Dari pengusaha berkelanjutan hingga pendukung toko barang bekas, dari pembeli sadar hingga pemilik toko lokal, pandangan mereka berkonvergensi pada satu realitas: pakaian cepat murah, tetapi biaya sebenarnya jauh lebih besar.
"Orang tidak menyadari bahwa Nepal bisa segera menjadi tempat pembuangan limbah pakaian," kata Rewati Gurung, pendiri Kokroma, sebuah usaha sosial yang memproduksi pakaian anak-anak berbahan kapas. Karya Gurung berakar pada pemulihan praktik tradisional dalam membuat pakaian yang dahulu dibuat dengan perhatian dan bahan alami. Baginya, mode berkelanjutan bukan hanya tentang kain ramah lingkungan; itu tentang komunitas, sirkularitas, dan tanggung jawab.
Pakaian Kokroma diproduksi sepenuhnya di lembah Kathmandu, mulai dari tenun dan pencelupan hingga penyelesaian, sehingga menjaga jejak karbon tetap rendah. Sisa kain digunakan kembali menjadi selimut dan kasur, memastikan proses tanpa limbah. Namun, meskipun Gurung percaya bahwa bisnis berkelanjutan dapat berkembang, ia khawatir tentang greenwashing oleh perusahaan pakaian cepat yang berpura-pura etis. "Itu merugikan kami lebih dari persaingan itu sendiri," katanya.
Seperti Gurung, Priya Sigdel, co-founder HattiHatti Nepal, memandang mode sebagai pilihan gaya hidup yang lebih luas. "Bagi kami, ini selalu tentang konsumsi yang sadar dalam setiap aspek kehidupan," katanya. HattiHatti merekrut perempuan dari komunitas yang terpinggirkan dan individu dengan disabilitas, mengubah limbah tekstil menjadi tas belanja, aksesori, dan pakaian. Model mereka menggabungkan pemberdayaan dengan daur ulang, meredefinisikan mode sebagai alat inklusi dan perawatan lingkungan.
Kedua pengusaha tersebut melihat harapan. Gurung percaya konsumen Nepal pada akhirnya akan beralih ke pilihan yang lebih halus dan bermakna, seperti orang-orang di Australia yang berpindah dari pakaian cepat setelah dua dekade. Sigdel membayangkan mode berkelanjutan berpindah dari khusus ke utama dalam lima hingga sepuluh tahun, didukung oleh insentif kebijakan dan kesadaran konsumen.
Tetapi keduanya juga melihat risiko dari ketidakaksaraan. Tanpa regulasi, Nepal bisa akhirnya menanggung beban limbah pakaian dunia sementara tradisi dan lingkungan sendiri harus membayar harganya.
Jika peringatan para pengusaha terasa abstrak, karya 'Sukhawoti Store' membuatnya menjadi nyata. Didirikan pada tahun 2016, toko ini memiliki lima cabang di Lembah Kathmandu dan satu di Pokhara, menjual pakaian, sepatu, buku, dan barang rumah tangga bekas dan didaur ulang. Donasi berasal dari rumah tangga, kotak drop-off, dan layanan pengambilan gratis.
Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, Sukhawoti telah merekayasa ulang atau mendaur ulang lebih dari 152 ton tekstil, mencegahnya mencapai tempat pembuangan sampah. Namun, seperti yang dijelaskan oleh CEO Chitra Dahal, meningkatnya pakaian jadi murah impor dari Tiongkok dan Thailand telah memperumit misi mereka. "Kami kewalahan dengan donasi, tetapi sebagian besar berupa kualitas rendah dan tidak bisa dijual," katanya. Biaya pengurutan dan pembuangan telah meningkat tajam, menggerus margin keuntungan mereka yang sudah sempit.
Beban lingkungan sangat besar. Pakaian sintetis yang tidak dapat dijual kembali dibuang atau dibakar, melepaskan racun ke tanah, sungai, dan udara. Mikroplastik meresap ke sistem air, sementara zat warna kimia menghasilkan air limbah yang beracun. Sistem pengelolaan sampah Nepal, yang sudah rapuh, tidak mampu mengikutinya.
Daur ulang dan daur ulang kembali menawarkan solusi - mengalihkan tekstil dari tempat pembuangan sampah, mengurangi polusi, dan menciptakan pekerjaan lokal - tetapi infrastruktur masih kurang. Nepal tidak memiliki fasilitas daur ulang tekstil skala besar, sehingga perusahaan seperti Sukhawoti harus berjuang sendirian. Di sisi lain, stigma budaya masih ada: pakaian bekas sering dianggap sebagai simbol kemiskinan, meskipun semakin diterima oleh konsumen muda.
Dahal meminta solusi sistemik: infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik, dukungan pemerintah bagi usaha daur ulang, dan pajak "hijau" terhadap pakaian cepat impor. Tanpa hal-hal ini, ia khawatir Nepal akan tenggelam dalam pakaian yang tidak bisa ditangani.
Tidak semua konsumen mengabaikan masalah ini. Lekhani Niraula, fellow peneliti di SAARC, yang secara teratur membeli pakaian bekas, melihat mode sebagai sesuatu yang personal dan bermakna. Baginya, memakai kemeja ayahnya atau menemukan gaun bekas dengan harga sebagian dari harga ecerannya adalah murah dan ramah lingkungan. "Ini seperti pencarian harta karun," katanya. Bagi Niraula, keberlanjutan bukanlah tentang pengorbanan tetapi kreativitas—menggabungkan barang antik dengan temuan thrift untuk membangun gaya unik.
Tetapi dia mengakui merasa frustrasi dengan bagaimana berbelanja barang bekas semakin dikomersialkan. Beberapa toko menaikkan harga pakaian bekas secara signifikan hingga pembeli mulai bertanya-tanya apakah barang pakaian cepat baru lebih murah. Bagi sebuah gerakan yang dimaksudkan untuk membuat pakaian terjangkau dan mudah diakses, pergeseran menuju praktik mencari keuntungan ini terasa seperti pengkhianatan.
Di sisi lain, pakaian cepat tetap memegang kendali atas banyak konsumen muda. Payal Prasai, seorang mahasiswa di King's College, membeli pakaian yang sedang tren dari grosir Tiongkok dan India karena harganya murah dan selalu berubah. Platform media sosial seperti TikTok dan Instagram meningkatkan permintaan akan penampilan baru setiap musim. Dampak lingkungan jarang terlintas dalam pikirannya. "Jujur, sebagian besar dari kami tidak pernah memikirkan hal itu saat berbelanja," katanya. "Kami lebih memperhatikan harga dan penampilan."
Jika pakaian berkelanjutan lebih terjangkau, Prasai mengakui dia mungkin akan beralih. Tapi sampai saat itu tiba, pilihan antara kemeja berharga Rs250 dan alternatif etis berharga Rs1.500 adalah hal yang mudah bagi kebanyakan teman sebayanya.
Pengecer lokal terjepit antara permintaan konsumen dan pergeseran sistemik.
Radhika Gaire, pemilik Radhika Fancy Shop di Koteshwar, telah menjual pakaian selama delapan tahun. Awalnya, bisnis berjalan baik. Ia mempertahankan margin keuntungan yang rendah, berharap dapat menyediakan pakaian yang terjangkau bagi pelanggan. Namun dengan pasokan pakaian murah dari supplier Tiongkok yang membanjiri pasar, persaingan telah menurunkan keuntungan.
"Pelanggan tidak ingin pakaian bermerk," katanya. "Mereka ingin opsi yang paling murah, memakainya dua atau tiga kali untuk video TikTok, lalu beralih ke yang lain." Sekarang dia menjual lebih banyak pakaian rumah seharga Rs250 daripada barang lainnya, meskipun dia menyediakan barang bernilai Rs3.000. Kualitas kalah penting dibandingkan harga.
Bagi para grosir seperti Kundan Shah dari Sasto Bazaar di New Baneshwar, mode cepat adalah sebuah sistem. Agen membeli lot yang tidak terjual dari pasar Tiongkok dengan harga setengahnya dan mengimpornya ke Nepal, di mana barang-barang tersebut melewati distributor dan pengecer. Ini adalah rantai pasok yang dirancang untuk volume, bukan keawetan. Shah merasa sedikit ancaman dari mode berkelanjutan. "Yang memengaruhi kami adalah bisnis, bukan ini," katanya. Baginya, selama permintaan akan pakaian murah tetap tinggi, model bisnis ini akan bertahan.
Munculnya mode cepat di Nepal mencerminkan tren global tetapi dengan sisi yang lebih tajam. Nepal tidak memiliki infrastruktur industri seperti Bangladesh atau Tiongkok, tetapi menghadapi kerentanan lingkungan yang serupa. Tanpa kebijakan yang kuat, pakaian impor membanjiri pasar, mengalahkan produsen lokal sambil meninggalkan limbah yang tidak dapat dikelola oleh sistem tersebut.
Pengusaha seperti Gurung dan Sigdel sedang membangun alternatif yang berakar pada tradisi, komunitas, dan tanggung jawab. Perusahaan seperti Sukhawoti Store menunjukkan bahwa ekonomi sirkular bisa bekerja tetapi membutuhkan dukungan sistemik. Pembeli sadar seperti Niraula membuktikan bahwa keberlanjutan bisa menjadi praktis dan personal. Namun, daya tarik pakaian murah yang didorong oleh media sosial, tekanan teman sebaya, dan keterjangkauan terus membuat pembeli muda seperti Prasai setia pada rak pakaian cepat.
Pemerintah berada di persimpangan jalan. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri jangka pendek dengan menarik produksi pakaian atau berinvestasi dalam ketahanan jangka panjang dengan mendukung industri berkelanjutan, infrastruktur daur ulang, dan kesadaran konsumen. Pilihan ini akan membentuk tidak hanya ekonomi Nepal tetapi juga lingkungan, budaya, dan identitasnya.
Pada akhirnya, perdebatan tentang pakaian cepat di Nepal bukanlah tentang tren, tetapi tentang nilai-nilai. Apakah kita mengukur kemajuan berdasarkan jumlah pakaian yang diproduksi dan dikonsumsi, atau berdasarkan kesehatan sungai-sungai kita, martabat pekerja kita, dan kreativitas komunitas kita?
Sementara Nepal terlibat dalam rantai pasok global, risiko menjadi pusat polusi dan limbah yang lain semakin nyata. Namun demikian, kemungkinan untuk menempuh jalur yang berbeda juga semakin besar—di mana mode bukanlah sesuatu yang sekali pakai, tetapi tahan lama; bukan eksploitatif, tetapi pemberdayaan; bukan diimpor, tetapi berakar pada tanah Nepal.
Pakaian yang kita kenakan menceritakan kisah. Pertanyaannya adalah apakah Nepal ingin ceritanya menjadi satu tentang konsumsi dan pemborosan yang tak berkesudahan, atau satu tentang ketangguhan, tanggung jawab, dan pembaruan.





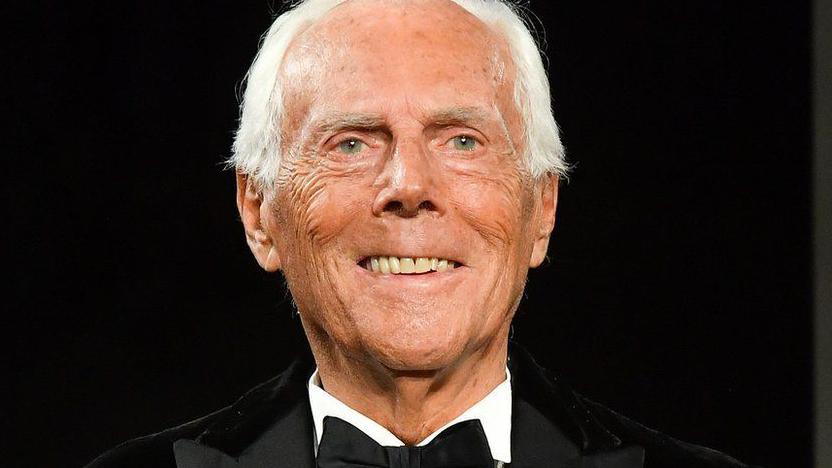
















Komentar
Tuliskan Komentar Anda!