
Krisis Perguruan Tinggi di Tengah Perubahan Global
Beberapa bulan terakhir, isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggemparkan kampus-kampus di Indonesia. Protes yang muncul dari berbagai daerah menunjukkan bahwa perguruan tinggi kita sedang menghadapi krisis serius. Alih-alih menjadi pusat pencarian ilmu dan pembentukan karakter, banyak kampus justru tergelincir menjadi “pabrik gelar” yang tunduk pada logika pasar.
Sejak Plato mendirikan Akademia di Athena lebih dari dua ribu tahun lalu, pendidikan tinggi dipandang sebagai pilar peradaban. Universitas Bologna, Paris, Oxford, hingga model riset ala Wilhelm von Humboldt di abad ke-19, semuanya berakar pada semangat kebebasan intelektual, riset yang berdampak, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Di Indonesia, nilai-nilai tersebut terwariskan dalam bentuk Tridarma Perguruan Tinggi: pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pertanyaan pentingnya adalah apakah perguruan tinggi kita masih setia pada esensi itu di tengah Revolusi Industri 4.0 dan lahirnya masyarakat super cerdas – Society 5.0?
Perguruan Tinggi Sebagai Aktor Ekonomi
Dalam praktik, perguruan tinggi di banyak negara berubah menjadi aktor ekonomi. Mahasiswa dipandang sebagai konsumen, program studi dijual sebagai produk, dan ilmu pengetahuan diperlakukan bak komoditas. Jepang bisa jadi cermin. Setelah Perang Dunia II, negeri itu hanya memiliki sekitar 50 universitas. Kini jumlahnya melonjak jadi lebih dari 800. Namun, populasi usia kuliah terus menurun: dari 1,2 juta orang pada 2020 diproyeksikan hanya 800 ribu pada 2040. Akibatnya, kampus-kampus berebut mahasiswa dengan strategi pemasaran, mulai dari mengganti nama jurusan hingga promosi besar-besaran.
Indonesia menghadapi tantangan berbeda. Populasi usia kuliah masih besar, tetapi masalah kualitas, kurikulum yang tak relevan, dan lemahnya keterhubungan dengan kebutuhan masyarakat membuat universitas kita rapuh. Perguruan tinggi negeri dan swasta tumbuh pesat, tetapi kualitasnya timpang. Alih-alih memperkuat peran universitas sebagai laboratorium ide, pemerintah justru sibuk mendorong liberalisasi dengan klasterisasi perguruan tinggi negeri (PTN)—Satker (Satuan Kerja), BLU (Badan Layanan Umum), hingga PTN-BH (Berbadan Hukum). Di balik narasi otonomi, ada kecenderungan negara melepas tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Disrupsi Teknologi dan Perubahan Kurikulum
Latar krisis juga datang dari disrupsi Revolusi Industri 4.0: kecerdasan buatan, big data, Internet of Things, dan robotika. Teknologi ini mengubah cara belajar. Pendidikan tidak lagi bisa sekadar menekankan hafalan, tetapi harus melatih keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi global. Jepang merespons dengan gagasan Society 5.0, yaitu masyarakat super cerdas yang menempatkan teknologi bukan hanya untuk efisiensi, melainkan juga untuk memecahkan masalah sosial: ketimpangan, kesehatan, dan lingkungan.
Dalam dunia pendidikan, kita telah melewati fase pembelajaran 1.0 yang berpusat pada guru, 2.0 yang menekankan diskusi, 3.0 dengan integrasi teknologi digital, hingga 4.0 yang bersifat personal, adaptif, dan berbasis kecerdasan buatan. Perubahan ini menuntut perguruan tinggi di Indonesia untuk tidak lagi sekadar mencetak lulusan siap kerja, tetapi juga melahirkan generasi yang mampu merumuskan solusi nyata bagi persoalan masyarakat.
Menatap Masa Depan
Dennis Gabor, peraih Nobel Fisika, pernah berpesan: masa depan tidak diramalkan, melainkan diciptakan. Perguruan tinggi karenanya perlu membangun foresight, kemampuan menatap masa depan secara sistematis. Ada lima langkah kunci (Nissen dkk., 2020). Pertama, environmental scanning, membaca tren global: demografi, teknologi, iklim, hingga politik. Kedua, scenario building, menyusun kemungkinan masa depan dalam versi optimis, moderat, dan pesimis. Ketiga, backcasting, merumuskan langkah mundur dari visi masa depan ke kondisi saat ini. Keempat, visioning, membangun visi kolektif universitas. Kelima, strategic action, mengimplementasikan kebijakan berbasis data dan kolaborasi.
Ambil contoh Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah ini masih menghadapi gizi buruk, stunting, dan ketergantungan pada sektor primer. Melalui foresight, universitas di NTT bisa merumuskan visi optimis: pada 2045 menjadi pusat riset agritech tropis dan energi terbarukan. Langkah backcasting berarti menyiapkan laboratorium berbasis AI untuk riset pangan, beasiswa berbasis daerah agar talenta lokal tidak migrasi, serta jejaring riset dengan pemerintah dan industri. Visi besar yang dapat dirumuskan adalah menjadikan NTT sebagai center of excellence dalam ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan energi berkelanjutan.
Menentukan Wajah Pendidikan Tinggi
Krisis perguruan tinggi Indonesia bukan sekadar soal jumlah mahasiswa, melainkan juga soal identitas: apakah ia masih laboratorium ide atau sekadar pabrik gelar. Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 menuntut kampus kembali pada hakikatnya: pusat pencarian kebenaran, inovasi, dan transformasi sosial. Plato memberi pesan abadi: universitas adalah ruang kebijaksanaan. Kini, kita ditantang memilih: apakah perguruan tinggi Indonesia tetap setia pada amanat Tridarma, atau tunduk sepenuhnya pada logika pasar. Jawaban atas pilihan ini akan menentukan wajah pendidikan tinggi Indonesia dalam beberapa dekade ke depan.



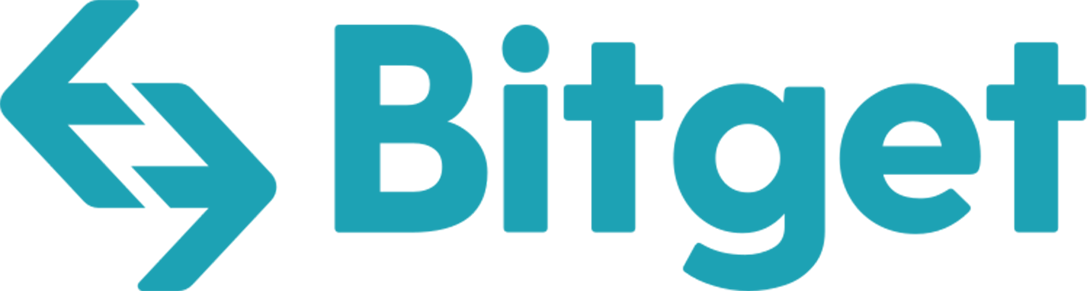


















Komentar
Tuliskan Komentar Anda!